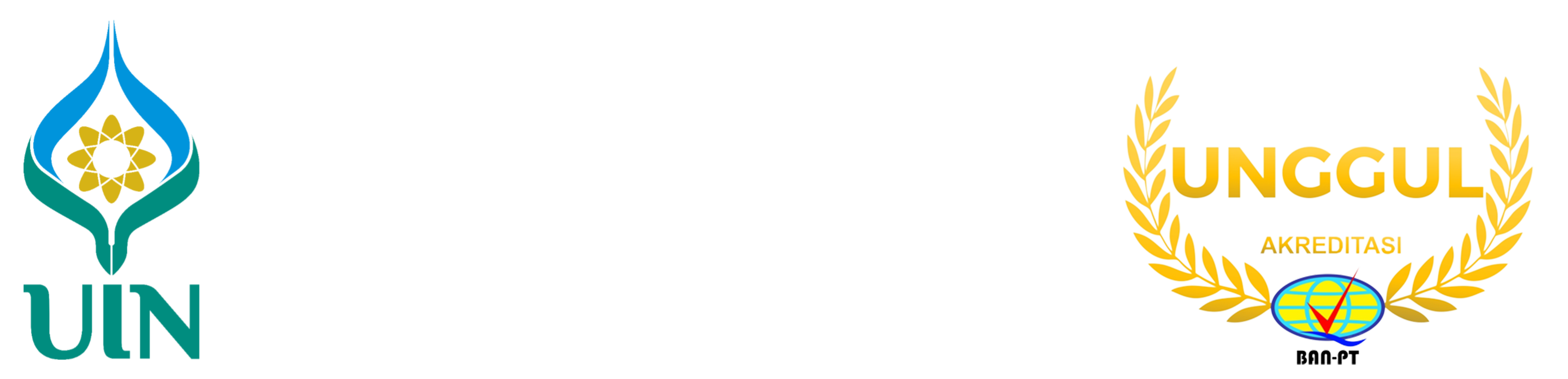Relasi Keberislaman-Kebangsaan dan Globalitas-Lokalitas, Aktualisasi Spirit Kepahlawanan dalam Diri Generasi Muda
Prof. Dr. H. Wardani, M.Ag.
“Pahlawanku teladanku, terus bergerak, melanjutkan perjuangan”
(Tema Hari Pahlawan, 10 November 2025)
Pahlawan: Cerminan Jiwa Kebangsaan
Setiap tanggal 10 November, kita sebagai warga negara Indonesia yang sadar akan jasa perjuangan para pahlawan memperingati hari Pahlawan. Pada tanggal 10 November 1945, telah terjadi pertempuran besar di Surabaya. Ketika itu, para pahlawan melawan tentara sekutu yang terdiri dari Inggris dan Belanda yang ingin melanggengkan penjajahan atas negeri ini. Pasukan Indonesia dipimpin oleh Bung Tomo dan para tokoh lainnya menghalau sekutu. Beberapa tokoh Islam, seperti K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Wahab Hasbullah, dan beberapa kiyai lainnya ikut menggerakkan para santri melawan kekuatan asing. Peristiwa ini menggambarkan sikap heroik para pahlawan.
Bung Tomo sendiri, sebutan untuk Sutomo (3 Oktober 1920 – 7 Oktober 1981), sang penggerak itu, pada 10 November 1945, baru berusia 25 tahun dan ia memimpin perlawanan rakyat Surabaya pada peristiwa tersebut. Usia tepatnya di tanggal tersebut adalah 25 tahun, 1 bulan, dan sekitar 7 hari. Bung Tomo ketika itu tergolong muda.
Keberislaman dan Kebangsaan
Sudah lama kaum Muslimin terlibat dalam perlawanan penjajah di negeri ini. Jasa mereka tidak diragukan lagi. Kini, semangat kepahlawanan itu seharusnya diwarisi oleh generasi muda. Kelompok terakhir inilah yang menyambut estafet pemimpin bangsa. Pejuang bangsa tidak hanya terbatas pada sosok perang 10 November, melainkan juga mereka yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, seperti Sukarno, M. Hatta, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Agus Salim, dan sebagainya.
Beberapa ayat dalam al-Qur`an mengajak kita untuk menginternalisasikan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai patriotisme kebangsaan dalam diri. Generasi muda berada di depan dalam usaha mewujudkan generasi islami sekaligus patriotis. Mereka harus meneladani perjuangan para pahlawan yang berjuang secara totalitas untuk negeri ini, tanpa pamrih.
Visi keberislaman dan kebangsaan dianjurkan untuk diwujudkan dalam al-Qur`an:
يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ
Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (Al-Qur’an surah Al-Ḥujurāt ayat 13).
Makna Global Ayat
Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki (Adam) dan seorang perempuan (Hawa) dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit bukan untuk saling mencemoohkan, tetapi supaya saling mengenal dan menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kepangkatan, atau kekayaannya karena yang paling mulia di antara manusia pada sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa kepada-Nya.
- Takwa: Keberislaman Sejati
Ayat berbicara keberislamaan, dan inti keberislaman adalah ketakwaan, dan ketakwaan menjadi sumber kemuliaan. Ketakwaan adalah inti atau dimensi paling mendalam dari keberislaman. Siapa pun yang mengaku beriman, namun tidak menghayati nilai-nilai ketakwaan di dalamnya, maka akan menjadi kosong-melompong. Ibarat iman tanpa amal, sama dengan keberislaman tanpa ketakwaan.
“Takwa” adalah dimensi terdalam, dimensi spiritual dari ajaran Islam. Takwa sering didefinisikan sebagai “melaksanakan perintah Allah swt, dan meninggalkan larangan-Nya”. Namun, takwa bukan sekadar pelaksanaan perintah dan menghindari larangan, melainkan sikap batin yang tunduk, merendah, dan menyerahkan diri (submission) kepada sang Khāliq. Seorang muslim mungkin ia adalah “saleh secara ritual” dalam pengertian melaksanakan perintah Allah swt, namun tidak berarti bahwa ia telah menjadi muslim sejati jika tidak dilengkapi penghayatan batin. Sisi lain dari takwa adalah pengamalan ajaran moral. Dengan begitu, takwa juga “saleh secara spiritual” (penghayatan batin” dan “saleh secara moral” (berakhlak mulia).
Kebiasaan manusia memandang kemuliaan itu selalu ada sangkut-pautnya dengan kebangsaan dan kekayaan. Padahal menurut pandangan Allah, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa kepada-Nya.
Diriwayatkan oleh Ibnu Ḥibbān dan at-Tirmiżī dari Ibnu ‘Umar bahwa ia berkata:
Rasulullah saw melakukan tawaf di atas untanya yang telinganya tidak sempurna (terputus sebagian) pada hari Fatḥ Makkah (Pembebasan Makkah). Lalu beliau menyentuh tiang Ka‘bah dengan tongkat yang bengkok ujungnya. Beliau tidak mendapatkan tempat untuk menderumkan untanya di masjid sehingga unta itu dibawa keluar menuju lembah lalu menderumkannya di sana. Kemudian Rasulullah memuji Allah dan mengagungkan-Nya, kemudian berkata, “Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan pada kalian kesombongan dan keangkuhan Jahiliah. Wahai manusia, sesungguhnya manusia itu ada dua macam: orang yang berbuat kebajikan, bertakwa, dan mulia di sisi Tuhannya. Dan orang yang durhaka, celaka, dan hina di sisi Tuhannya. Kemudian Rasulullah membaca ayat: yā ayyuhan-nās innā khalaqnākum min żakarin wa unṡā… Beliau membaca sampai akhir ayat, lalu berkata, “Inilah yang aku katakan, dan aku memohon ampun kepada Allah untukku dan untuk kalian. (Riwayat Ibnu Ḥibbān dan at-Tirmiżī dari Ibnu ‘Umar). (Tafsir Kemenag RI)
- Keberislaman, Ketakwaan, dan Kebangsaan
Ayat di atas sangat menyentuh dimensi kemanusiaan secara universal. Mengapa? Pertama, ayat ini dibuka dengan “wahai manusia!”, bukan “wahai orang-orang yang beriman”. Ini menandakan bahwa yang menjadi audiens atau subjek yang dituju oleh ayat ini adalah semua manusia, dari berbagai kalangan, dengan latar belakang agama, ekonomi, dan sosial yang berbeda.
Kedua, ayat berbicara tentang kejadian manusia, yaitu yang terlahir dari pasangan laki-laki (suami) dan perempuan (istri). Pertanyaannya kemudian adalah untuk apa Tuhan melalui al-Qur`an ini mengingatkan manusia akan kejadian (penciptaan) ini?
Muhammad Asad dalam karyanya, The Message of the Qur`ān (h. 794), berkomentar terhadap potongan ayat ini dengan mengatakan, “We have created every one of you of a father and a mother” (Zamakhsharī, Rāzī, Baydāwī)-implying that this equality of biological origin is reflected of human dignity common to all.” Menurutnya, potongan ayat ini menjadi asal-usul kejadian manusia secara biologis yang menunjukkan bahwa martabat manusia itu pada prinsipnya manusia”. Artinya, setiap manusia terlahir ke dunia pada prinsipnya sama dan setara. Ia adalah manusia yang sama harakat dan martabatnya dengan manusia yang lain. Bahkan, Zamakhsyarī, sebagaimana dikutip oleh Asad, menyatakan bahwa semua manusia berasal dari “keluarga” manusia yang sama juga tanpa ada superioritas bawaan yang melekat padanya yang melebihi antara satu dengan yang lainnya.
Ketiga, ayat ini juga berbiacara tentang perkembangan manusia menjadi kelompok-kelompok, dari skop yang paling kecil, seperti kabilah, suku, marga, dsb., hingga skop yang lebih besar, yaitu bangsa. Di sini, kita melihat pergeseran pembicaraan ayat, dari asal-usul kejadiannya dari pasangan ayah dan ibu, kini ke soal keberadaannya sebagai suku dan bangsa. Pergeseran ini sebenarnya secara simbolik ingin menunjukkan bahwa manusia-manusia setelah berkelompok sebagai suku dan bangsa seharusnya tidak untuk saling menegasikan/menafikan kelompok lain, sebagai suku atau bangsa, karena mereka pada hakikat asal yang sama (kesatuan asal-usul).
Itu artinya, solidaritas kesukuan dan kebangsaan yang “sempit” menjadi ashabīyah, yang muncul ke permukaan sebagai fanatisme kesukuan, keakuan golongan, superioritas atau keunggulan suatu aliran, atau semaknanya, secara implisit dilarang di sini, bahkan secara eksplisit dilarang. “Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum mendoronmu kemudian untuk tidak berlaku adil”, dan dalam Q.s. al-Qashash: 15 dinyatakan:
وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِۖ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهٖ ۙفَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِۖ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ
Dia (Musa) masuk ke kota559) ketika penduduknya sedang lengah. Dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki yang sedang berkelahi, seorang dari golongannya (Bani Israil) dan seorang (lagi) dari golongan musuhnya (kaum Firʻaun). Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk (mengalahkan) orang yang dari golongan musuhnya. Musa lalu memukulnya dan (tanpa sengaja) membunuhnya. Dia berkata, “Ini termasuk perbuatan setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang jelas-jelas menyesatkan.”
559) Menurut sebagian mufasir, kota itu adalah Memphis yang terletak di Mesir bagian utara.
Menurut Asad, ungkapan “perbuatan Setan” (min ‘amal al-syatithān) yang berkaitan dengan ayat 16-17, menunjukkan bahwa orang dari Bani Isrā`īl, bukan orang Mesir, adalah salah dalam hal ini, dengan memicu pemukulan/pembunuhan itu. Ayat ini menjadi bukti bahwa Allah swt melarang solidaritas kesukuan secara sempit yang kemudian mendorong perbuatan jahat (Asad, 591, fn. 15).
Keempat, tidak ada larangan bagi manusia untuk hidup sebagai suku atau sebagai bangsa, karena hal itu merupakan konsekuensi logis dan alamiah dari pertumbuhan jumlah manusia, sehingga perlu mengatur pemenuhan kebutuhan hidup secara baik dalam sebuah bangsa. Oleh karena itu, kesukuan dan kebangsaan tidak bertentangan dengan ide fitrah manusia dan tidak bertentangan dengan ide keislaman dan ketakwaan. Yang bertentangan dengan keduanya adalah penistaan terhadap kemanusiaan, seperti perlakuan tidak adil, diskriminasi, pembersihan etnik (ethnic cleansing), politik apartheid/ diskriminasi atas dasar warna kulit, segregasi gender, rasisme, dan sebagainya.
Sebaliknya, yang dijunjung tinggi oleh al-Qur`an adalah ketakwaan, yaitu komitmen untuk menjalankan ajaran Islam secara totalitas dan instrinsik, dengan tidak pengalaman formalitas atas ritual-ritualnya, melainkan memahami dimensi kehambaan kepada Tuhan dan menonjokan sisi moralitas, baik kepada sesama muslim maupun kepada sesama manusia. Dari persaudaraan atas dasar agama Islam (ukhūwah Islāmīyah) hingga persaudaraan sesama manusia (ukhūwah insānīyah).
Globalitas dan Lokalitas
Islam punya visi global sekaligus mengapresiasi khazanah lokal. Berpikir global tentang Islam berarti berwawasan luas tentang visi Islam yang menjangkau sisi-sisi Barat dan Timur, Islam Timur Tengah dan Islam Keindonesian. Visi global menjadikan Islam tidak berpikir sempit tentang kesukuan, solidaritas kelompok, rasisme, dan semaknanya, yang bertentangan ide universalitas ajaran Islam.
Misi global Islam, antara lain, disebutkan dalam al-Qur`an dengan mengatakan bahwa Nabi Muḥammad diutus sebagai “rahmat bagi semesta”, sebagaimana tampak dari Q.s. al-Anbiyā`: 107 berikut:
وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ
Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.
Kata “bagi semesta” (li al-‘ālamīn) melingkupi semua lapisan manusia dari berbagai suku dan bangsa dengan latar belakang beragam. Ayat ini berkaitan erat dengan pernyataan dalam Q.s. al-A’rāf: 158 yang menyatakan: “Katakan, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua…”. Konteks ayat ini sebenarnya berbicara tentang kisah Bani Musa dan Bani Isrā`īl yang menjelaskan ayat-ayat sebelumnya. Para rasul masa awal diutus hanya kepada komunitasnya saja. Perjanjian Lama hanya ditujukan kepada Bani Isrā`īl, dan Nabi Isa as pun disebutkan menyebut dirinya “diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Isrā`īl” (Matius xv: 24) (Asad, 227 fn. 126).
Meskipun demikian, pernyataan misi global nabi terdahulu juga disebut dalam al-Qur`an “Musa berkata: Wahai Fir’aun, sesungguhnya aku adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam” (Q.s. al-A’rāf: 104). Namun, syariat mereka terbatas dan bahkan direvisi oleh syariat Nabi Muhammad sebagai konsekuensi sebagai penutup para nabi. Berbeda dengan para rasul dan kitab suci-kitab suci yang diturunkan sebelumnya, Nabi Muhammad diutus kepada “semesta” atau kepada “seluruh manusia”, dan al-Qur`an yang dibawanya “menjadi petunjuk bagi (seluruh) manusia” (hudan li al-nās) (Q.s. al-Baqarah: 185).
Penegasan lebih lanjut tentang misi global kenabian Nabi Muḥammad ketika disebutkan (Q.s. al-Aḥzāb: 40): “(Dan ketahuilah, wahai orang-orang yang beriman), Muḥammad bukanlah ayah bagi seseorang di antara kalian, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi”. Maksudnya, Nabi Muhammad bukanlah ayah biologis bagi seseorang, yang dalam sejarah disebut Zaid sebagai anak angkat.[1] Muhammad Asad kemudian menafsirkan dengan kebalikannya, yaitu bahwa jika Nabi Muhammad bukanlah ayah biologis bagi seseorang yang kemudian diartikan mempersempit perhatiannya kepada semua umat Islam, maka justeru hal ini harus diartikan sebagai “Bapak spiritual” bagi semua komunitas.
Hubungan spiritual antara beliau dan orang-orang yang beriman disebutkan di bagian surah ini (Q.s. al-Aḥzāb: 6) bahwa “Nabi (Muḥammad) lebih utama dibandingkan orang-orang beriman dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Hubungan spiritual itu adalah karena Nabi Muḥammadlah orang yang diberikan wahyu oleh Tuhan yang kemudian setiap orang bisa memilih untuk mengikutinya. Kaum muslimin dibimbing oleh beliau, sehingga karena melaluinya, kaum muslimin mendapat petunjuk.
Oleh karena itu, tidak akan ada keimanan yang hakiki jika Nabi Muḥammad tidak dilibatkan dalam hal ini. Bahkan, sebagai ekspresinya, sebagian Sahabat beliau, seperti Ibn Mas’ūd, Ubayy ibn Ka’b, Ibn ‘Abbās, dan Mu’āwiyah hampir tidak pernah membaca ayat tersebut sebelum dijelaskan oleh Nabi (Asad, 639 fn. 8).
Meskipun misi Islam adalah misi global yang menyentuh semua masyarakat dengan latar belakang berbeda, namun Islam juga mengakui partikularitas budaya lokal. Di samping globalitas, al-Qur`an juga mengakui lokalitas. Dalam Q.s. Āl ‘Imrān: 104, dinyatakan sebagai berikut:
وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ
Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma’rūf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Menurut tafsir Kementerian Agama, ma’rūf adalah segala kebaikan yang diperintahkan oleh agama serta bermanfaat untuk kebaikan individu dan masyarakat. Mungkar adalah setiap keburukan yang dilarang oleh agama serta merusak kehidupan individu dan masyarakat.
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ
Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.
Menurut M. Quraish Shihab (Wawasan al-Qur`an, 342), kata ma’rūf dan ‘urf yang disebut di dua ayat di atas bermakna kebiasaan atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan “prinsip-prinsip ajaran Islam” (al-khayr yang disebut di ayat pertama di atas). Sesuai dengan makna awal secara kebahasaan, kedua kata itu semula bermakna “yang dikenal”, maksudnya adalah yang dikenal oleh masyarakat dan dipraktikkan oleh mereka, namun pemahaman dan praktik itu setidaknya tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.
Pemaknaan kedua istilah ini benar-benar bisa diterjemahkan sebagai tradisi atau adat istiadat (tidak bertentangan dengan Islam). Namun, menurut Hamka,[2] kedua kata itu bermakna sebagai penjabaran Islam ke dalam praktik-praktik masyarakat, itu artinya bermakna sebagai “tradisi/adat istiadat Islam” (ajaran-ajaran Islam dijabarkan di dalamnya), atau setidaknya “Islami” (nilai-nilai Islam diadopsi di dalamnya).
Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī, suatu ketika ‘A`isyah r. anha mengawinkan seorang gadis yatim dari kerabatnya dengan seorang pemuda dari Anshar (penduduk kota Madinah). Namun, dalam acara tersebut, tidak terdengar ada nyanyian. Nabi Muḥammad kemudian bertanya: “Apakah tidak ada permainan/nyanyian? Karena orang-orang Anshar senang mendengar nyanyian..” (Shihab, 343).
Penutup
- Generasi muda sekarang perlu menanamkan spirit kepahlawanan karena para pahlawan sang pembela Tanah Air ini merupakan teladan dalam hal totalitas membela bangsa ini dengan ketulusan. Mereka adalah teladan sejati.
- Para pahlawan telah meneladani kita akan pentingnya spirit kebangsaan, yaitu kesatuan dalam mempertahankan Tanah Air ini. Keberislaman tidak menjadi alasan secara eksklusif untuk merongrong negeri ini yang telah membesarkannya dan darah daging mereka adalah hasil saripati tanah dari negeri ini. Keberislaman bukan antitesis (lawan) terhadap kebangsaan, atau kebangsaan bukanlah lawan terhadap keberislaman, karena keberislaman sesungguhnya terletak pada ketakwaan, yaitu tidak hanya menjalan ajaran ritualnya, melainkan juga kesadaran spiritual (penghambaan diri kepada Allah swt) dan sikap moral (berakhlak mulia) sebagai intinya. Dengan begitulah, kemuliaan manusia bisa diraih.
- Meskipun Islam ditujukan kepada seluruh manusia dan misi Islam bersifat global, lintas ruang dan waktu, namun partikularitas budaya, tradisi, dan adat istiadat tidak bertentangan dengan “prinsip ajaran Islam”, atau bahkan yang merupakan penjabaran dari Islam sebagai tradisi Islam dan Islami.
- Dengan memahami semangat kemanusiaan, kebangsaan, dan pentingnya partikularitas budaya/tradisi/adat istiadat, generasi muda tidak hanya perlu mengamalkan ajaran-ajaran Islam, tapi perlu berpikir dan bertindak dalam koridor kemanusiaan (humanity), berintegritas terhadap bangsanya, dan menghargai budaya. Itulah nilai-nilai kepahlawanan yang diteladani oleh para pahlawan dan khususnya para pahlawan dari kalangan kiyai yang memerdekakan Tanah Air ini dari penjajah.
[1]Baca, sebagai bandingan, karya David S. Powers tentang hal ini, Muhammad is Not the Father of Any of Your Men.
[2]Lihat, lebih lanjutnya, uraian tentang hal ini, Wardani, Sosiologi al-Qur`an.
Tag:Hari Pahlawan, Opini Dosen, Wardani