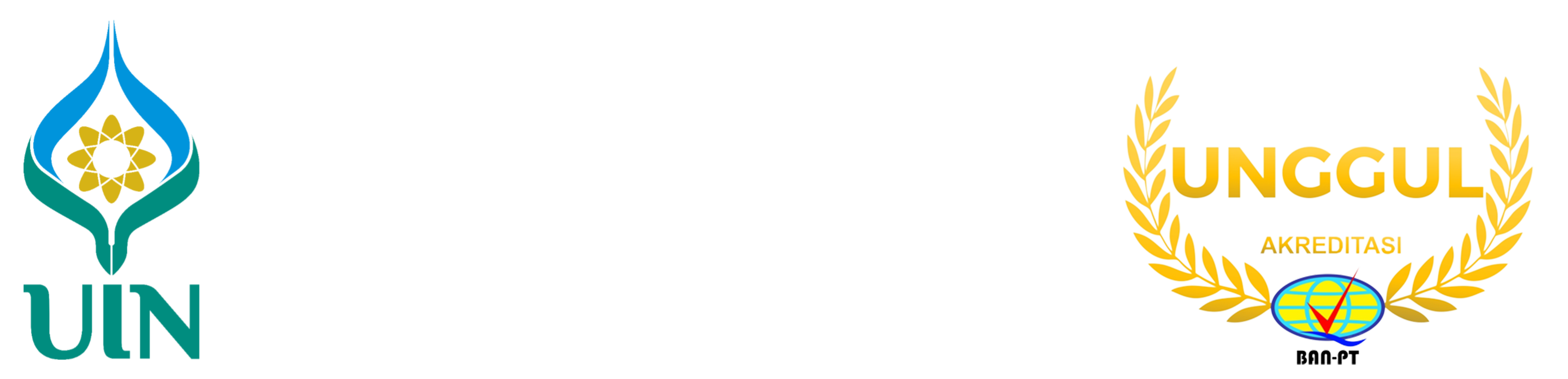Mempertanyakan Bonus Demografi
Tantangan dunia kerja merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat kita, dan lembaga pendidikan turut serta bertanggungjawab menyikapinya. Sebagai bahan renungan, di sini kami terbitkan ulang kolom-kolom rektor terkait topik tersebut.
MEMPERTANYAKAN BONUS DEMOGRAFI
Mujiburrahman
Kunjungan saya ke Brunei Darussalam pada 26-27 Juni 2023 lalu adalah untuk menghadiri konferensi yang diselenggarakan oleh Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) dan rapat Asian Islamic Universities Association (AIUA). Setelah kegiatan selesai, saya menyempatkan diri untuk bertemu dua ilmuwan asal Indonesia yang kini bekerja di Universiti Brunei Darussalam (UBD): ahli ekonomi dan demografi, Aris Ananta (Pak Aris), dan ahli demografi dan statistik sosial, Evi Nurvidya Arifin (Bu Evi).
Saya pertama kali bertemu mereka pada November 2022 silam melalui seorang teman yang juga akademisi di UBD. Meski baru kenal, kami langsung akrab. Kali kedua ini, saya dijemput mereka ke hotel dan diajak ke sebuah restoran untuk makan-minum sambil berbincang. Dalam perbincangan itulah saya banyak belajar dari keahlian dan pengalaman hidup mereka. Salah satu yang saya dapatkan adalah pandangan mereka terhadap konsep ‘bonus demografi’ yang semakin sering kita dengar dan baca di media, yang disampaikan oleh para pejabat pemerintah ataupun akademisi.
Saya mengatakan bahwa saya tidak paham betul apa yang dimaksud dengan bonus demografi itu. “Kalau Bapak bingung, itu pertanda baik. Kami juga bingung,” kata bu Evi sambil sedikit tertawa disambut senyum oleh Pak Aris. Pak Aris kemudian menjelaskan bahwa konsep bonus demografi itu mengandung asumsi-asumsi yang perlu dipertanyakan. Jika tidak, maka kita akan mudah terperangkap dalam harapan-harapan palsu tentang masa depan, seolah-olah bonus demografi otomatis adalah berkah. Sesungguhnya bonus itu belum ada, masih harus diperjuangkan.
Konsep bonus demografi mengatakan bahwa penduduk usia 15-64 tahun adalah usia produktif, dan ketika jumlah mereka banyak, maka terjadilah semacam nilai tambah kependudukan. Pertanyaannya, benarkah asumsi bahwa dalam usia 15-64 tahun itu penduduk kita ini benar-benar produktif? Belum tentu. “Bukankah pada usia 15-24 tahun, banyak anak di Indonesia masih tergantung pada orangtua, diongkosi selama menjalani pendidikan?” kata Bu Evi. “Begitu pula, orang yang usianya di atas 64 tahun sebagian juga masih ada yang produktif,” kata Pak Aris.
Asumsi tentang usia produktif tersebut semakin bermasalah jika kita kaitkan dengan kesehatan dan pendidikan. Sekarang ini masih banyak masyarakat Indonesia yang mengalami gangguan kesehatan, fisik dan mental. “Bagaimana dengan jumlah tengkes (stunting) yang tinggi?” kata Pak Aris. Selain tengkes, masih banyak lagi masalah kesehatan yang kita hadapi. Selain itu, mutu dan tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap produktivitas. Bagaimanapun, produktivitas ada hubungannya dengan ilmu, keterampilan dan karakter seseorang yang dibina melalui pendidikan.
“Artinya, tingginya jumlah orang-orang yang layak bekerja itu justru dapat menimbulkan masalah serius, yakni pengangguran,” kataku. “Ya. Namun kita harus berhati-hati juga menafsirkannya. Jumlah pengangguran yang tinggi belum tentu menunjukkan kemiskinan. Di sejumlah negara makmur, angka pengangguran ternyata tinggi karena anak muda masih bisa bergantung pada orangtuanya atau karena penganggur mendapat santunan negara. Sebaliknya, di negara miskin, jika tidak bekerja orang akan kelaparan. Maka angka pengangguran bisa jadi rendah,” katanya.
Setelah berpisah dengan dua ilmuwan tadi, saya mencoba merenung, menghubungkan apa yang saya dapatkan di hari pertama konferensi. Ibrahim M. Zein dari Hamad bin Khalifa University, Qatar, mengisyaratkan dalam makalahnya bahwa dunia pendidikan harus memerhatikan pasar kerja. Saat rehat, Syekh Salama Jum’ah Ali Daoud dari Universitas al-Azhar mendebatnya. “Jika pendidikan mengikuti pasar kerja, maka ketika lapangan kerja tidak tersedia lagi untuk satu bidang ilmu, ilmu itu akan ditinggalkan. Ini tidak boleh terjadi. Pendidikan itu bukan soal kerja saja,” kata Syekh.
Ibrahim M. Zein berusaha menjelaskan pendapatnya. Dia mengatakan, sebenarnya yang dia inginkan adalah bagaimana agar pendidikan mendorong generasi muda untuk menciptakan lapangan kerja, bukan sebaliknya. Syekh tetap ngotot bahwa hubungan pasar kerja dan pendidikan tidak harus timbal-balik seperti itu. Apalagi jika menyangkut bidang ilmu kemanusiaan dan keagamaan. Saya kemudian menyela. “Mungkin Anda berdua sama-sama benar. Yang satu berbicara tentang pendidikan secara luas, sedangkan yang lain berbicara tentang pengajaran dan pelatihan,” kataku.
Esok harinya, Mufti Kesultanan Brunei, Haji Awang Abdul Aziz, menyampaikan pidato kunci. Dia mengutip konsep UNESCO tentang empat pilar pendidikan, yaitu (1) learning to know, belajar untuk menguasai ilmu; (2) learning to do, belajar untuk mengerjakan sesuatu); (3) learning to be, belajar untuk mandiri dan memaknai hidup; (4) learning to live together, belajar untuk hidup bersama dengan orang lain. Menurut Mufti, empat pilar ini sejalan dengan nilai-nilai Islam. Saya pun lega, karena perdebatan dua tokoh di atas tampaknya bisa selesai dengan pendapatnya ini.
Alhasil, daripada latah soal bonus demografi, saat ini yang perlu kita usahakan adalah meningkatkan mutu layanan pendidikan dan kesehatan semaksimal mungkin. Jika tidak, kelebihan penduduk usia layak kerja mungkin saja menjadi musibah, bukan berkah, dan kurang pas disebut ‘bonus demografi’.
10 Juli 2023
Artikel ini telah terbit di Banjarmasin Post dan dapat diakses melalui laman:
https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/10/mempertanyakan-bonus-demografi