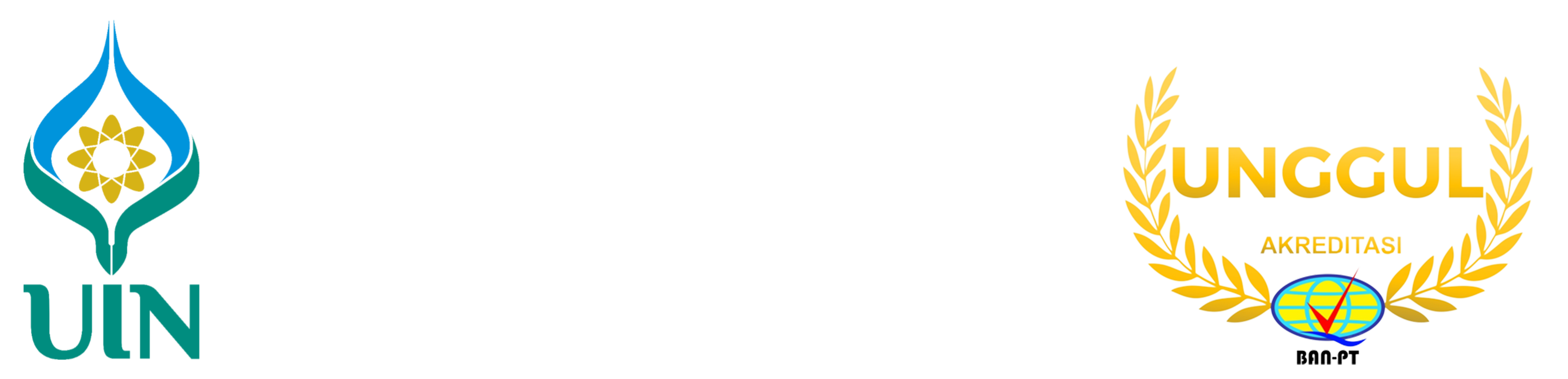Data BPS, Gus Dur, dan Kita
Tantangan dunia kerja merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat kita, dan lembaga pendidikan turut serta bertanggungjawab menyikapinya. Sebagai bahan renungan, di sini kami terbitkan ulang kolom-kolom rektor terkait topik tersebut.
DATA BPS, GUS DUR, DAN KITA
Mujiburrahman
“Realitas Kemiskinan Lebih Tinggi dari Data” adalah salah satu judul berita utama Kompas, 17 Januari 2025 kemarin. Menurut data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang miskin di Indonesia pada 2024 menurun, yakni 8,57 persen, jika dibandingkan dengan 2023 sebanyak 9,36 persen. Sepertinya, ini kabar baik dan menggembirakan. Tapi tunggu dulu.
Paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jumlah 8,57 persen itu sama dengan 24,06 juta penduduk. Satu jumlah yang amat besar. Kedua, selama 26 tahun (sejak 1998), pemerintah kita menggunakan standar yang sama untuk mengukur kemiskinan, yakni berpenghasilan Rp 595.242 per bulan, atau Rp 21.250 per hari. Standar ini lebih rendah dari negara-negara tetangga. Menurut Arief Anshori Yusuf, anggota Dewan Ekonomi Nasional, sebagaimana dikutip Kompas, jika kita menaikkan standarnya sama dengan Timor Leste saja, maka kemiskinan di Indonesia mencapai 30 persen!
Tak syak lagi, salah satu sebab utama di balik kemiskinan di negeri kita yang kaya ini adalah korupsi. Saya pun teringat pada buku kumpulan artikel Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terbit pada Desember 2024 lalu berjudul Insya Allah, Saya Serius. Salah satu artikel di buku ini, semula terbit di majalah Optimis No.30 (Juli, 1982), membahas tentang “kerja”. Gus Dur tidak membahas etos kerja dalam kerangka teologi perihal kebebasan versus kepasrahan manusia di hadapan kuasa Tuhan, tetapi lebih banyak menyoroti kesenjangan struktural dan kerapuhan akhlak masyarakat kita.
Yang disoroti Gus Dur adalah soal kesenjangan antara kata dan perbuatan, antara nilai-nilai moral yang ideal dan kenyataan hidup sehari-hari, terutama terkait korupsi. “Katakanlah soal korupsi. Itu tindakan yang tidak mulia, tidak normal, tapi bila semua orang melakukannya, maka akhirnya dianggap sebagai kenormalan tersendiri. Bila ada yang menggugat masalah iitu, orang akan menjadi geli, merasa lucu. Akibatnya, patokan-patokan moral bangsa, nilai-nilai yang kita anut, mengalami kemunduran besar. Batas antara yang baik dan yang buruk, lantas menjadi kabur” (40-41).
Kerapuhan moral itu terasa pula di kalangan orang-orang miskin yang berjuang untuk bertahan hidup dengan sesuap nasi. Mereka juga terbiasa culas. Gus Dur bertanya, “Apa hak bangsa untuk menuntut pemimpin-pemimpinnya jangan korupsi bila dia sendiri maling. Bila dia sendiri harus menipu orang, harus bergulat dengan sesuatu yang sangat periferal sifatnya: mencuri, merampok, mengambil hak orang dengan kekerasan, ‘korupsi kecil-kecilan’. Apakah dengan titik tolak seperti itu, mereka masih punya hak untuk menuntut sesuatu yang lebih tinggi, lebih luhur, kepada yang atas?” (39).
Gus Dur bahkan mencatat, kesenjangan antara kata dan perbuatan juga tampak pada sebagian ulama. Jika ada konflik antar-ulama, atau ada ulama yang berkhotbah tentang hidup sederhana, tetapi dia sendiri mengendarai mobil mewah, atau dia berpidato tentang kenakalan remaja, tetapi anaknya sendiri nakal, masyarakat biasa-biasa saja. “Biarkan saja dia omong begitu. Kita maklum deh. Toh akhirnya, problem dia sama saja dengan kita-kita ini,” tulis Gus Dur seolah mengutip mereka. “Padahal, dulu ulama-ulama yang seperti itu bisa dilempari batu,” kata Gus Dur (39-40).
Apakah di dalam lubuk hati yang terdalam, orang-orang itu tidak merasa bersalah? Bagi Gus Dur, hakikat diri manusia itu baik, dan suka kepada yang baik. Karena itu, mereka sebenarnya tetap tidak suka dengan korupsi, dan ada rasa marah dalam hati jika mengetahui kasus korupsi. “Walaupun diri sendiri ikut mengerjakannya, tapi bukan berarti mereka menerima, malah seringkali menyesali, mengapa bisa ikut-ikutan berkorupsi” (42). Jadi, ada semacam pertentangan batin yang ruwet di sini, antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dialami sendiri.
Pertentangan batin itu akhirnya melahirkan berbagai kepura-puraan. Moralitas disamakan saja dengan tata krama atau sopan santun. “Kehidupan lantas penuh dengan berbagai pretensi. Seseorang yang omong tentang moral tapi tidak bermoral, maka dia akan mencari substitusinya, misalnya dengan memakai tata krama. Tata krama lantas ditempatkan pada tempat moral. Ini sungguh-sungguh buruk. Yang kemudian terjadi adalah semacam pengakuan dosa secara massal, tanpa mengindentifikasi siapa pelakunya” (42).
Demikianlah pengamatan Gus Dur sekitar 42 tahun yang silam. Tampaknya kini kita masih mengalami masalah serupa meskipun tak sama. Politik uang berjalan lancar karena mayoritas pemilih kita miskin. Pejabat menjadi korup karena biaya politik tinggi. Dia harus menyiapkan uang untuk bertarung dalam pemilu. Jika tak punya uang sendiri, dia harus pinjam kepada orang kaya. Akibatnya, orang kaya semakin berkuasa, baik langsung di dalam negara atau di luar negara. Keadaan menjadi makin parah ketika para penegak hukum justru memperjualbelikan hukum. Muncullah mafia hukum.
Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaikinya? Gus Dur dengan jelas menunjukkan bahwa masalah utama di balik semua ini adalah kerapuhan moral dan kebangkrutan akhlak. Jika kita ingin berubah, maka kita harus mengubah kemunafikan menjadi kejujuran, ikut-ikutan menjadi teguh pendirian. Tentu saja, ini tidak semudah mengatakan dan menuliskannya. Namun, sesulit apapun itu, kita harus insaf bahwa jika kita tidak mau berubah atau tidak peduli, maka cepat atau lambat kehancuran akan datang menjemput kita!
20 Januari 2025
Artikel ini telah terbit di Banjarmasin Post, dan dapat diakses di laman berikut: https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/20/data-bps-gus-dur-dan-kita