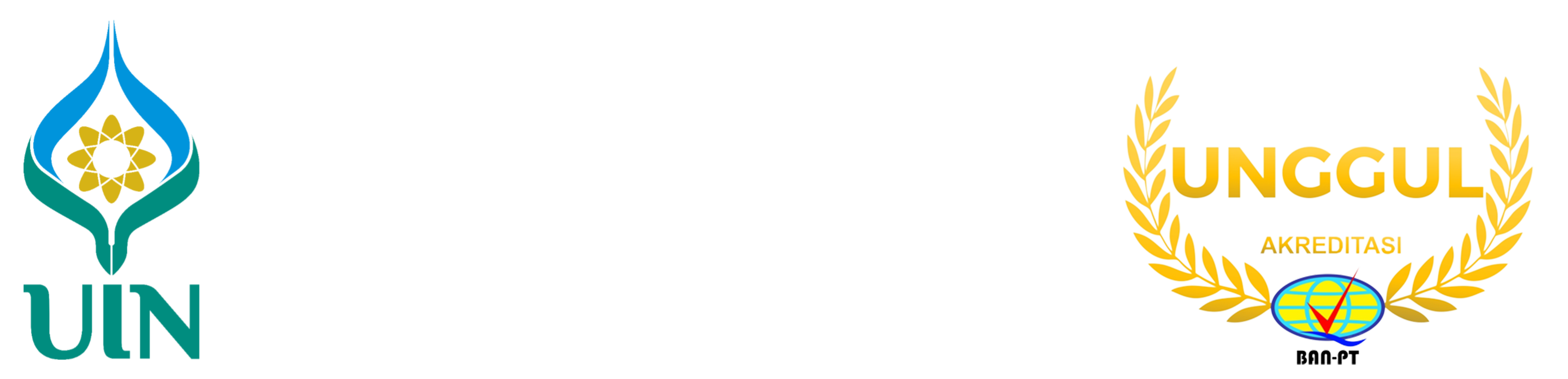Wajah Islam di UIN: Antara Transformasi, Ambiguitas, dan Harapan Baru
Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.
(Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin)
TRANSFORMASI IAIN menjadi UIN adalah salah satu perubahan paling besar dalam sejarah pendidikan tinggi Islam Indonesia. Perubahan ini lahir dari kebutuhan zaman: membuka akses akademik lebih luas, memperkaya disiplin ilmu, dan membuat kampus Islam dapat berkompetisi di tingkat global. Namun, di balik keberhasilan administratif dan perluasan fakultas, ada satu isu yang jarang dibicarakan secara terbuka: bagaimana wajah Islam kampus ini terbentuk di mata publik setelah transformasi tersebut?
Pada masa ketika institusi masih bernama IAIN, wajah Islam begitu jelas dan tegas. Para rektor dan sebagian besar dosen adalah ulama yang dihormati masyarakat. Figur-figur seperti Harun Nasution, Quraish Shihab, atau Azyumardi Azra (pada masa awal transformasi) bukan hanya akademisi, tetapi simbol moral, rujukan fatwa sosial, dan panutan umat. IAIN dikenal sebagai “rumah ilmu dan ulama”—tempat di mana keilmuan dan keulamaan berjalan beriringan tanpa keraguan.
Namun ketika IAIN berubah menjadi UIN, wajah publik tersebut ikut mengalami pergeseran. Dengan perubahan regulatif yang memberi kewenangan Menteri Agama menunjuk rektor, syarat keulamaan perlahan bukan lagi unsur dominan. Para rektor bisa dipilih dari akademisi yang unggul secara manajerial dan administratif, namun tidak selalu memiliki legitimasi keulamaan di masyarakat. Transformasi struktural ini, meski memberi peluang bagi tata kelola modern, secara simbolik membuat publik bertanya: di mana wajah ulama dalam institusi pendidikan Islam yang kini semakin menyerupai universitas umum?
Problem pertama yang muncul adalah krisis identitas simbolik. UIN tetap membawa embel-embel “Islam Negeri”, namun figur keagamaannya tidak lagi sejelas ketika masih IAIN. Di ruang publik, masyarakat sering membandingkan: dulu rektor IAIN adalah tokoh yang khotbahnya ditunggu, fatwanya diikuti, dan nasihatnya dirindukan. Kini, sebagian rektor UIN lebih tampil sebagai birokrat terdidik—kapabel, tetapi tidak selalu menjadi wajah religius yang dikenal publik.
Problem kedua adalah ketidakjelasan jalur representasi Islam melalui ilmu. Sejak era Isma’il Raji al Faruqi dengan gagasan Islamization of Knowledge, wacana tentang integrasi ilmu agama dan ilmu modern menjadi arus besar dalam dunia pendidikan Islam. Namun dalam praktiknya, implementasi pada banyak UIN masih parsial. Integrasi ilmu sering berhenti pada moto, struktur kurikulum, atau label-label fakultas. Upaya untuk benar-benar melahirkan epistemologi ilmiah bercorak Islam yang autentik masih berjalan terpatah-patah.
Dalam konteks ini, pemikiran Ziauddin Sardar tentang Islamic Science—yang menekankan pembentukan sains alternatif berbasis nilai Islam, humanitas, dan kritik peradaban Barat—belum banyak mewarnai riset-riset saintifik di UIN. Fakultas-fakultas sains di berbagai UIN memang berkembang pesat, namun belum menghasilkan narasi besar yang menegaskan perbedaan etis dan epistemologi antara “sains sekuler” dan “sains Islami”. Dengan kata lain, jalur kedua dalam menampilkan wajah Islam melalui ilmu pengetahuan belum menemukan bentuk yang kokoh.
Problem ketiga adalah transisi budaya akademik. Ketika UIN membuka fakultas teknik, kedokteran, psikologi, dan ekonomi modern, terjadi pelebaran spektrum kompetensi dosen, mahasiswa, dan orientasi akademik. Namun pelebaran ini tidak otomatis melahirkan budaya kampus yang lebih islami secara keilmuan. Ada kampus yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam tata kelola dan kurikulum modern, tetapi ada pula yang terjebak pada dualisme identitas: tampilan modern di satu sisi, simbol Islam normatif di sisi lain, tanpa integrasi yang mendalam.
Di mata masyarakat luas, kondisi ini sering melahirkan ambiguitas: apakah UIN adalah universitas Islam dengan wajah ulama? ataukah universitas umum yang kebetulan membawa nama Islam? atau sedang mencari jalan tengah yang belum selesai?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena identitas keislaman sebuah lembaga pendidikan tidak hanya ditentukan oleh nama institusi, tetapi oleh konsistensi nilai, figur, kepemimpinan, produk ilmiah, dan kontribusinya kepada masyarakat.
Namun semua ini bukan semata cerita keprihatinan. Transformasi juga membuka jalan harapan. UIN memiliki potensi besar untuk memadukan keulamaan klasik dengan kepakaran modern. Banyak dosen muda yang menempuh pendidikan doktoral di Timur Tengah, Eropa, dan Amerika, yang membawa pulang wacana baru tentang integrasi ilmu, maqāṣid sharī‘ah, etika teknologi, dan humanisme Islam. Fakultas-fakultas sains berkembang dengan laboratorium dan riset yang semakin kompetitif. Ke depan, tugas besar UIN adalah menemukan kembali wajah Islamnya yang khas—yang bukan nostalgia ke masa IAIN, tetapi bentuk baru yang sesuai tuntutan zaman.
Untuk itu, tiga agenda strategis perlu ditegakkan:
- Pemulihan legitimasi moral melalui kepemimpinan yang memiliki kredibilitas akademik sekaligus keulamaan.
- Integrasi ilmu yang nyata, bukan simbolik—melalui riset lintas disiplin, epistemologi Islam yang kuat, dan orientasi etis terhadap ilmu modern.
- Komunikasi publik yang konsisten, agar masyarakat mengerti arah pengembangan UIN dan tetap melihatnya sebagai pusat ilmu, nilai, dan moralitas Islam.
UIN berada pada persimpangan sejarah. Ia bisa menjadi pionir kebangkitan pendidikan Islam, atau kehilangan identitasnya di tengah arus modernisasi yang tanpa arah. Tantangannya besar, tetapi harapannya jauh lebih besar. Wajah Islam masa depan kampus ini ditentukan oleh pilihan-pilihan akademik dan moral hari ini.